ADA masa ketika pakaian semata-mata soal fungsi. Ia hadir untuk melindungi tubuh dari dingin atau panas, untuk menjaga kesopanan di ruang sosial, atau menjadi bagian dari ritual budaya dan spiritual. Tapi seiring waktu, pakaian berevolusi menjadi sesuatu yang lebih kompleks: simbol status, penanda kelas, bahkan bentuk kekuasaan simbolik.
Kini, fashion bukan lagi sekadar soal “selera.” Ia telah menjadi bahasa yang menunjukkan siapa kita—atau setidaknya, siapa yang ingin kita tampilkan kepada dunia. Ia berbicara tentang kelas sosial, akses, dan kelayakan. Dalam masyarakat kapitalistik hari ini, harga sebuah pakaian tidak selalu mencerminkan kualitas bahan atau kesulitan pengerjaannya, melainkan nilai simbolik yang dibebankan padanya.
Tas tangan bermerek kini disebut sebagai “investasi,” bukan karena kekuatannya menampung barang, melainkan karena kekuatannya menandai status. Jaket tertentu bukan lagi pelindung tubuh, tetapi penanda afiliasi sosial. Singkat kata, logo telah mengalahkan fungsi.
Sebelum revolusi industri, pakaian dibuat secara personal. Perempuan dari kelas petani dan pekerja menjahit sendiri baju mereka. Kaum bangsawan dan keluarga kerajaan memesan pakaian dari penjahit profesional, yang dibuat dengan tangan-tangan para pengerajin dan disesuaikan secara presisi.
Mode tetap ada—tapi mode berarti menyesuaikan kerah, menambah renda, atau mengganti potongan, tak berarti membeli gaun baru setiap musim. Ekslusivitas itu hanya untuk kelas atas.

Dunia fashion saat itu adalah dunia tertutup, eksklusif, dan elitis. Mode ditentukan oleh bangsawan, istri tuan tanah, selebritas zaman itu, dan para desainer istana. Tapi semua berubah saat revolusi industri menciptakan mesin jahit, mempercepat produksi kain, dan—yang paling berdampak—menstandarkan tubuh manusia menjadi ukuran S, M, L.
Dari sinilah lahir konsep ready-to-wear (prêt-à-porter). Untuk pertama kalinya, masyarakat luas bisa membeli pakaian jadi tanpa perlu menjahitnya lebih dulu atau menunggu berhari-hari hingga penjahit menyelesaikannya. Bahkan rumah mode mewah seperti Dior dan Chanel pun kini punya lini ready-to-wear untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.
Namun kemudahan itu datang dengan harga tinggi: eksploitasi tenaga kerja, limbah tekstil, dan pencemaran lingkungan menjadi bagian tak terhindarkan dari produksi massal.
Jika ready-to-wear adalah industrialisasi dalam balutan estetika mewah, maka fast fashion adalah bentuk paling brutal dari kapitalisme mode. Brand seperti Zara, H&M, hingga SHEIN mengubah ritme mode dari musiman menjadi mingguan. Produksi dilakukan secara masif, cepat, dan sangat murah.
Satu desain bisa hadir dalam puluhan warna, beragam potongan, dan diperbarui dalam hitungan hari. Tujuannya bukan agar kita memenuhi kebutuhan dasar berpakaian, tetapi agar kita merasa harus membeli, dan membeli lagi. Di sinilah muncul apa yang disebut banyak peneliti sebagai ilusi pilihan—kita merasa diberi kebebasan untuk memilih, padahal sebenarnya diarahkan pada satu hal: konsumsi terus-menerus.

Di balik harga murah itu, tersembunyi ironi: baju-baju fast fashion tidak dibuat untuk bertahan. Ambil contoh SHEIN, pemain dominan dalam ekosistem mode cepat ini. Banyak pembeli melaporkan bahwa pakaian dari SHEIN rusak hanya setelah beberapa kali cuci. Ini bukan kebetulan—fast fashion tidak didesain untuk dipakai ulang, melainkan untuk dibuang dan diganti.
Kualitas rendah ini sengaja dipertahankan untuk menciptakan siklus konsumsi tanpa akhir. Model bisnisnya bukan menyediakan pakaian, tapi menjual rasa harus beli sekarang, sebelum tren berlalu.
Dampaknya? Gunungan sampah tekstil. Setiap tahun, jutaan ton pakaian bekas dan tak terjual menumpuk di tempat-tempat seperti Gurun Atacama di Chili, yang kini dikenal sebagai “kuburan mode dunia.” Sebagian lainnya dikirim ke negara-negara Afrika, seperti Ghana dan Kenya, dengan dalih donasi, padahal kenyataannya adalah limpahan limbah mode dari negara-negara Utara.
Menurut laporan BBC dan Al Jazeera, hanya sekitar 10-20% dari pakaian bekas yang diekspor ke Afrika yang benar-benar dipakai. Sisanya dibakar, dikubur, atau mencemari ekosistem lokal. Sungai tersumbat, tanah rusak, dan masyarakat lokal menanggung beban ekologis yang bukan mereka ciptakan.

Fast fashion tampak seperti demokratisasi gaya—tapi sejatinya, ia adalah jebakan kapitalisme yang paling banal: memproduksi rasa “tidak cukup,” lalu menawarkan solusi dalam bentuk diskon dan kolonialisme baru dalam bentuk limbah.
Di sisi lain spektrum, gaya hidup elite abad ke-18 belum mati. Ia bereinkarnasi menjadi haute couture, atau adibusana. Ini adalah tingkatan fashion tertinggi: pakaian dijahit hanya untuk satu orang, dengan tangan, dalam waktu berbulan-bulan, dan hanya oleh rumah mode yang terdaftar resmi di Fédération de la Haute Couture et de la Mode.
Couture memang lebih berkelanjutan. Ia tidak diproduksi massal, limbah nyaris nol, dan dibuat dengan kualitas tinggi. Tapi apakah ini solusi? Tentu tidak untuk sebagian besar populasi dunia. Couture adalah bentuk paling mahal dari “green luxury” — ramah lingkungan. Couture hanya bisa diakses oleh mereka yang bisa membayar harga setara rumah.
Selain itu adibusana sering kali hanya tampil dalam satu gala, satu karpet merah, atau satu editorial majalah. Setelah itu, ia digantung di lemari privat, masuk arsip, atau bahkan dihancurkan demi menjaga eksklusivitas. Bukankah ini bentuk lain dari pemborosan yang dibungkus kemewahan dan kesadaran ekologis?

Di sinilah ironi keberlanjutan muncul. Ketika eco-fashion dijadikan bagian dari gaya hidup elite, keberlanjutan menjadi citra, bukan kesadaran. Ia menjadi simbol prestise, bukan tanggung jawab kolektif.
Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar pergeseran gaya, tapi pergeseran nilai. Kapitalisme telah menciptakan sistem yang bukan hanya menjual barang, tapi menjual rasa: rasa kurang, rasa tertinggal, rasa ingin dianggap.
Inilah yang disebut para teoritikus budaya sebagai kapitalisme afektif. Sistem ini memanipulasi emosi konsumen untuk menciptakan permintaan yang tidak riil. Kita diajari bahwa memiliki baju terbaru adalah bentuk keberhasilan pribadi. Kita diberi pesan halus bahwa mengenakan pakaian lama adalah bentuk kegagalan kelas.
Padahal, dulu, pakaian yang tahan lama dianggap bijak dan fungsional. Memperbaiki pakaian adalah hal biasa. Sekarang, baju lama disebut “ketinggalan zaman,” dan memperbaiki pakaian dianggap “tidak stylish.” Kita tidak lagi membeli karena butuh, tapi karena tidak ingin terlihat usang di mata algoritma media sosial.
Tentu, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan individu. Kita semua hidup dalam sistem yang mendesain pilihan kita. Tapi bukan berarti kita tak punya kuasa. Kita bisa merebut kembali makna fashion sebagai ekspresi nilai, bukan gengsi.
Memilih membeli lebih sedikit, memperbaiki baju lama, thrifting, membeli dari produsen lokal, menyewa baju untuk acara tertentu, atau memilih bahan yang tahan lama—semua ini bisa jadi bentuk perlawanan kecil. Mungkin tidak cukup untuk menumbangkan sistem, tapi cukup untuk menandai bahwa kita tidak lagi menjadi konsumen pasif.
Kita bisa berhenti bertanya “Apa tren musim ini?”, dan mulai bertanya:
“Siapa yang sungguh-sungguh “membayar” harga dari baju yang saya pakai ini?”***
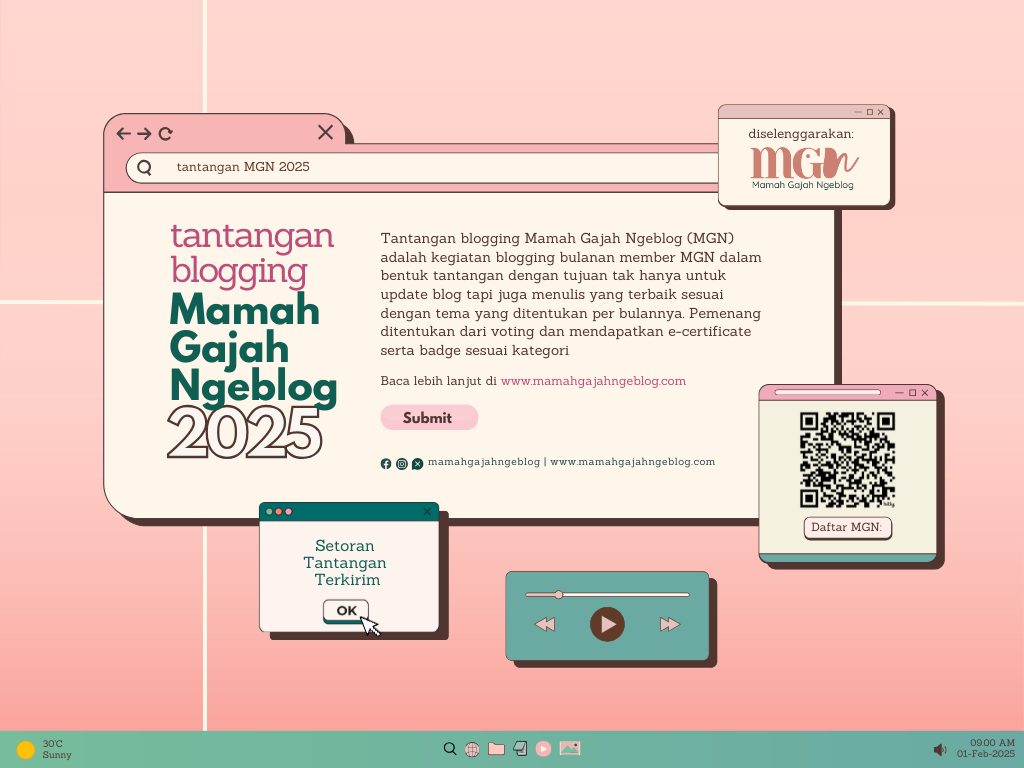
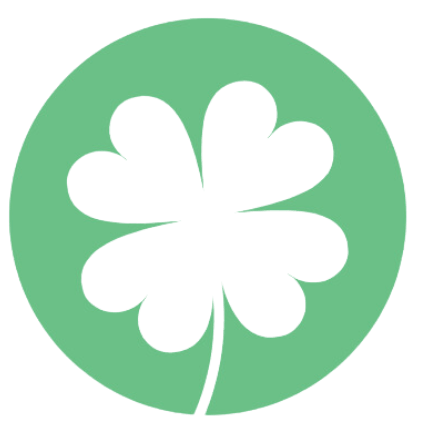





Tinggalkan Balasan ke Patricia Herdita Batalkan balasan